Sumatra Tempo Dulu nan Memikat
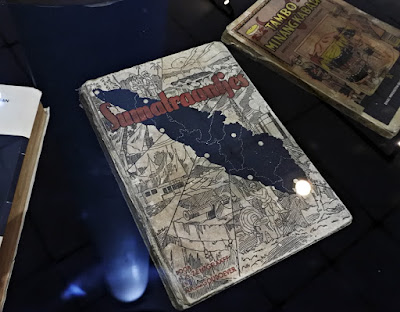 |
| Buku "babon" pameran foto “Warna-warni Kehidupan Sumatra 1947” |
Narasi tentang Pulau Sumatra tersaji dalam selembar poster
A0 yang ditempel di dinding dekat penerima tamu. Tak begitu nyaman dibaca
karena ukuran font terlampau kecil dengan jarak baca kurang ideal. Namun,
informasi di dalamnya menarik untuk dilihat sebelum menikmati pameran foto “Warna-warni
Kehidupan Sumatra 1947”.
Seperti pameran-pameran sebelumnya yang digelar di Bentara
Budaya Yogyakarta, saya memulai “perjalanan” ke Sumatra 1947 secara pradaksina
(searah jarum jam). Foto-foto yang dipamerkan merupakan reproduksi dari buku
lama seperti, Tanah Air Kita karya N.
A. Douwes Dekker (1950), Pusaka –Art of
Indonesia- From The Collection of National Museum dengan editor Didier
Millet (1990), dan Sumatraanjes karya
H. C. Zentgraaf (1936).
Melancong ke Bumi
Andaliman
Foto berjudul, “Buku-buku Nujum”, menyita perhatian saya.
Seorang lelaki dengan tutup kepala yang unik bertelanjang dada. Di bahu kirinya
tersampir kitab berbahan bambu yang memuat aksara dan gambar dengan makna
tertentu. Di keterangan foto disebutkan bahwa masyarakat Batak sudah tidak
menggunakan kitab ini lagi.
Di sampingnya ada foto seekor kuda dengan seorang lelaki
berdiri di sampingnya. Lelaki itu mengenakan blangkon, beskap, dan kain batik.
Unsur Jawa sangat kental dalam penampilannya. Namun, saya bertanya-tanya kuda
cantik ini didatangkan dari mana ke tanah Batak? Apakah mereka punya kuda
semacam sandel di Sumba?
 |
| Ahli nujum |
Puluhan perahu “parkir” di pantai yang sangat tenang. Hanya
ada sebuah rumah tak jauh dari barisan perahu. Lalu dua pohon besar dengan
tajuk tak cukup rindang. Di sekitarnya ramai orang berkerumun serupa semut.
Setelah melihat judu foto, ternyata foto itu menggambarkan suasana hari pasaran
di Prapat, tepi Danau Toba. Wah, ramai juga ya hari pasaran di Toba. Hebatnya,
mereka tak membangun pondok atau semacamnya yang bisa melindungi diri dari
panas. Para pedagang ngemper dan
pembeli berdiri berkerumun di dekatnya. Karena belum ada drone, kemungkinan besar foto ini diambil dari atas bukit.
Pulang Kampung
“Akhirnya ada Jambi juga,” ujar saya spontan begitu melihat
foto berjudul “Sungai Batanghari di Jambi”. Ada dua pompong besar dan satu pompong
kecil bersandar di –semacam- rumah apung. Sebuah kapal besar melintas di
belakangnya. Ah, ingatan saya langsung tertuju pada coklat air Batanghari
dengan getek (perahu kecil) di atasnya. Teringat bagaimana saya harus
menyebrangi sungai terpanjang di Sumatra ini nyaris setiap hari dulu saat
menyelesaikan tugas akhir. Seketika, setitik rindu terbit di sudut hati.
Masih di sungai, yang tak begitu jelas namanya, sekitar
empat perahu dengan bentuk yang unik sandar di dermaga kecil. Perahu-perahu itu
milik BPM (Bataafse Petroleum Maatschappij). “Emang kalau di Jambi ada minyak
juga ya?” tanya seorang teman yang pergi ke pameran bersama saya.
Kilang-kilang
minyak di daerah Tempino langsung hadir dalam bayangan visual saya. Betapa
hingga sekarang saya tak pernah ingin tahu tentang sejarah perminyakan di
Jambi. Hanya sesekali saja dengar rumor bahwa pipa minyak Pertamina sering “dibocori”
untuk dicuri minyaknya. Juga selintas mengamati kehadiran para pekerja minyak
dari Petrochina Oil yang seliweran di bandara. Saya cukup terkejut ketika isu
minyak ini jadi sorotan kurator pameran. Sesuatu dari Jambi yang dipilih untuk
ditampilkan dalam pameran ini.
 |
| Di atas Sungai Batanghari |
Jika saya acuh dengan minyak di Jambi, maka foto pabrik teh
Kayu Aro membuat mata berbinar. “Sebagai bekal jika satu saat berkunjung ke
sana,” saya membatin. Memang sudah sangat lama saya begitu ingin menjelajahi
tanah Kerinci. Ingin tahu cerita teh yang konon digemari ratu Inggris itu.
Bicara tentang Jambi tak lengkap jika tak mengundang Suku
Anak Dalam. Maka citra Jambi dalam pameran ini digenapkan oleh kehadiran foto seorang
lelaki Suku Anak Dalam yang berpose di tepi jalan. Hanya mengenakan cawat, ia
memegang semacam lembing di tangan kanannya. Di kanan dan kirinya membentang
pepohonan serupa hutan. Mungkin sekarang sudah jadi perkebunan sawit. Tak ada
info lebih tentang lelaki ini.
Perspektif Kolonial
Terhadap Aceh
Foto-foto untuk merepresentasikan Aceh sebagian besar berupa
potret diri tokoh dari kalangan atas. Ada Panglima Polim, seorang lelaki, dan
hulubalang Pantai Barat Aceh. Yang menarik perhatian saya ialah tutup kepala
yang dikenakan oleh mereka. Semua mengenakan topi rajut yang nyaris serupa. Apakah
sekarang mereka masih mengenakan topi yang sama?
“Rumah Orang Aceh yang Kurang Beruntung” saya pikir menjadi
foto paling menarik dari semua foto yang dipamerkan kali ini. Sebuah rumah
panggung beratapkan jerami, mungkin dengan dinding gedhek berdiri di tepi
sungai dengan perbukitan jadi latarnya. Ada beberapa pohon kelapa menjulang
tinggi. Sebatang pohon durian atau sialang turut meramaikan rimbun pepohonan di
sekitar rumah. Tapi, mengapa fotografer memilih judul seperti itu?
Apa yang salah dengan rumah ini? Ada banyak bahan pangan
tersedia di sekitarnya. Kelapa tinggal petik, durian (jika bukan sialang) atau
madu (jika bukan durian) tinggal ambil, ikan tinggal pancing, pemandangan
menyenangkan. Lalu di mana “kurang beruntungnya”?
 |
| "Kurang Beruntung" |
Judul ini menarik karena memberikan label berdasarkan
perspektif kulit putih. Bisa jadi hal ini masih terus direproduksi. Stigma
bahwa rumah berbahan bambu, gedhek, atau kayu sebagai rumah orang miskin
tampaknya masih dipelihara. Padahal bisa jadi mereka menggunakan bahan-bahan
atau teknik panggung untuk merespon lingkungan yang sering gempa atau terkena
banjir misalnya.
Lalu, anggapan bahwa tinggal bersama lingkungan pohon kelapa
atau kebun tidaklah menarik dibandingkan dengan tinggal di dalam komplek yang
nyaris tanah permukaannya ditutup konblok. Bahwa tinggal di desa dengan halaman
luas, pepohonan rindang, bahan pangan tinggal ambil di sekitar, tetap saja dianggap
“miskin” dibanding dengan orang-orang yang tinggal di kota. Hantu pelabelan
miskin dan kaya ini semakin subur disemai oleh sinetron-sinetron sampah yang
selalu hidup di rumah-rumah orang di desa.
Minangkabau yang
Memukau
“Kata Bapakku, daerah yang harus kukunjungi di Sumatra itu
ialah Sumatra Barat. Gila! Menarik banget,” ujar teman saat kami melihat foto
kehidupan di Sumatra Barat. Memang, daerah ini sudah masuk dalam daftar kunjung
saya sejak lama. 10 tahun yang lalu, saya hampir datang ke provinsi ini. Namun,
karena urusan pemilu saya batal singgah ke sini. Dan hingga kini belum juga ada
tanda untuk melancong ke sana.
 |
| "Memikat" |
Tiap daerah di Sumatra pasti kaya warna budaya. Namun, entah
mengapa Sumatra Barat selalu jadi prioritas saya. Tetangga provinsi tempat saya
lahir ini mampu menguarkan wangi aroma rempah begitu saya membayangkannya.
Solok, Bukittinggi, Padang, Pariaman, Lima Puluh Kota, dan masih banyak lagi
tempat di sana yang ingin saya jelajahi. Mencicipi ragam kuliner kaya rempah
dan singgah ke kampung Tan Malaka. Memang tak cukup seminggu untuk mengenal
daerah yang pernah didiami oleh Adityawarman ini. Seorang penguasa Melayu yang
foto arcanya juga ditampilkan dalam pameran ini.
Menerbangkan Asa
Menebar Hasrat
Jika dilihat lagi, pameran fotografi tetap saja masih
mengandalkan prinsip “foto mewakili seribu kata”. Begitu pula yang saya amati
dalam “Warna-warni Kehidupan Sumatra 1947” ini. Hanya ada judul foto dan
lokasi. Terkadang memang ada sedikit penjelasan lengkap terkait foto. Namun,
jangan berharap banyak untuk mendapatkan cerita terkait objek yang difoto.
Untuk alur cerita foto, mungkin akan lebih baik jika
ditampilkan berdasarkan kategori batas wilayah. Misal memulai dari Aceh atau
sebaliknya dari Lampung baru kemudian merunut ke daerah-daerah di sisi selatan
atau utaranya. Susur Sumatra dengan logika jalur darat bagi saya lebih
menyenangkan karena tidak perlu lompat-lompat. Ketika saya memulai dari Batak
kemudian diselingi Sumatera Barat dan Riau lalu singgah lagi ke Tapanuli,
rasanya kok rada capek ya. Hehehe. Padahal hanya melihat foto bukan singgah
langsung ke tempat-tempat itu.
Andai saja pameran ini disajikan dengan pendekatan
interpretasi maka pastinya akan jauh lebih menarik. Saya bisa betah
berlama-lama di sini karena ada koneksi dengan tanah kelahiran. Kurang tahu
kalau pengunjung yang lain. Namun, pastinya akan sangat disayangkan jika
kunjungan ini hanya terjebak pada citra “mooi indie” yang dibangun dalam
foto-foto yang dipamerkan. Kecuali foto “Rumah Orang Aceh yang Kurang Beruntung”
ya :D.
Namun, meskipun tak pakai interpretasi, pameran ini tetap
berhasil membuat saya makin ingin singgah ke tempat-tempat lain selain Jambi.
Tinggal lebih lama dan menanggalkan perspekstif “mooi indie”. Saya ingin
mengenal lebih dalam lingkungan dan orang-orang yang membangun kebudayaan di
bumi Suwarnadwipa ini. Semoga. Berucap saja dulu, siapa tahu akan nyata dalam
waktu mendatang.


Comments